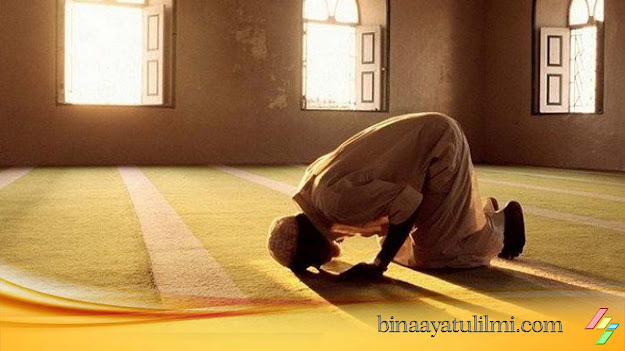by : Muhammad Saiyid Mahadhir, Lc, MAAllah swt berfirman:
إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي
“Sesungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan (yang hak) selain Aku, Maka sembahlah aku dan dirikanlah shalat untuk mengingat aku” (QS. Thaha: 14)
Ada tiga pokok pembahasan pada ayat di atas:
[Pertama]
Ayat ini adalah penutup kisah tentang kerasulan nabi Musa as setelah sebelumnya Musa melarikan diri dari kejaran orang-orang yang akan membunuhnya hingga akhirnya sampai ke suatu negri yang bernama Madyan. Ibnu Katsir dalam Qashash Al-Anbiya menuturkan[1], sembari duduk istirahat, Musa melihat ada dua orang perempuan yang sedang berusaha mengambil air, untuk minum ternaknya, namun terhalang karena mulut sumur tidak bisa diakses karena adanya batu besar yang menghalanginya.
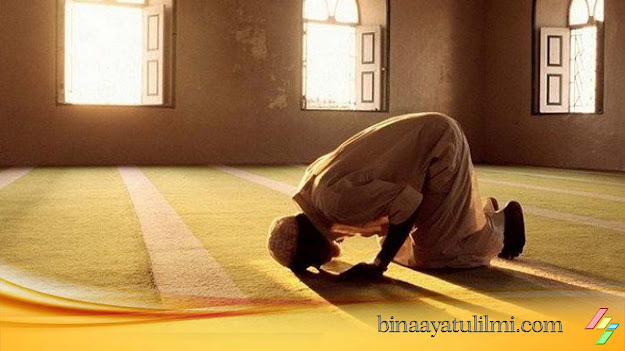
Musa akhirnya membantu keduanya, mengangkat batu itu sendirian yang biasanya batu tersebut diangkat oleh sepuluh orang, dan setelah itu, tanpa bayak basa-basi Musa kembali duduk istirahat. Kejadian hari itu diceritakan kembali oleh kedua perempuan tadi dengan ayahnya yang itu tak lain adalah nabi Syuaib as[2]. Musa kemudian diminta untuk menemui ayah dari kedua peremuan tersebut untuk diberi upah atas budi baiknya. Namun nabi Musa memilih jalan lain, beliau dengan penuh kemuliaan akhirnya bersedia dirinya “disewa” untuk menjadi pengembala kambing milik nabi Syuaib, demi menjaga kehormatan dirinya dan perutnya.
Tawaran itu bermula dari ide yang dilontarkan oleh anak perempuan nabi Syuaib as, setelah sebelumnya mereka semua mendengar cerita Musa bahwa sesungguhnya keberadaan di negri Madyan itu karena lari dari kejaran Firaun, tanpa ada persiapan sama sekali, sehingga bekal pun tidak ada.
Salah satu dari kedua anak perempuan itu berkata:
قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ
Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya".(QS. Al-Qasash: 26)
Umar bin Khattab ra berkata, ini juga riwayat dari Ibnu Abbas ra, Syuraih, Abu Malik, Qatadah, Muhammad bin Ishaq, dan banyak lagi yang lainnya menceritakan bahwa ketika mendengar perkataan anaknya, nabi Syuaib as berkata: “Dari mana ananda mengetahui bahwa Musa adalah orang yang kuat dan dapat dipercaya?” Lalu kemudian anaknya berkata: “Musa dengan sendirian berhasil mengangkat batu besar yang menutupi mulut sumur yang biasanya batu sebesar dan seberat itu diangkat oleh orang sepuluh, lalu ketika dalam perjalanan menuju ke rumah, awalnya saya yang berjalan didepan dan Musa mengikuti dari belakang, lalu Musa meminta agar beliau yang berjalan didepan dan saya dibelakang, jika beliau salah jalan cukup lempar saja batu kecil, tanpa saya harus berkata-kata”[3]
__________
Demikian kuat fisik yang digambarkan dengan mampu mengangkat batu besar sendirian, dan dapat dipercaya yang digambarkan dengan sikap yang sangat mulia, diawali dengan menjaga pandangan, dan menjaga pendengaran, yang bisa membuat jiwa terperosok kedalam dosa. Bahasa anak sekarang, kalau mata dan pendengaran saja bisa dijaga karena khawatir jiwa berdosa, apalagi hanya sebatas menjaga dan mengembala kambing, tidak mungkin rasanya Musa akan menipu mereka.
Akhirnya nabi Syuaib as menawarkan:
قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ
Berkatalah Dia (Syu'aib): "Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun Maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, Maka aku tidak hendak memberati kamu. dan kamu insya Allah akan mendapatiku Termasuk orang- orang yang baik". (QS. Al-Qasash: 27)
Musa mengiyakan:
قَالَ ذَلِكَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ أَيَّمَا الْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلَا عُدْوَانَ عَلَيَّ وَاللَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلٌ
Dia (Musa) berkata: "Itulah (perjanjian) antara aku dan kamu. mana saja dari kedua waktu yang ditentukan itu aku sempurnakan, Maka tidak ada tuntutan tambahan atas diriku (lagi). dan Allah adalah saksi atas apa yang kita ucapkan" (QS. Al-Qasash: 28)
Dari semenjak saat itu hingga sepuluh tahun kedepan, menutut pendapat yang paling kuat, Musa bekerja dengan nabi Syuaib, menjadi pengembala kambing. “Para nabi dan Rasul itu jika berkata (berjanji) dia akan melakukannya/menetapinya”, demikian Imam Al-Bukhari meriwayatkan sabda Rasulullah saw.
[Kedua]
Setelah sepuluh tahun bekerja dengan nabi Syuaib as, dan menikah dengan salah satu anak perempun beliau yang umurnya paling muda, Musa meminta izin kepada nabi Syuaib as untuk kembali/pulang kampung ke Mesir, alasan sederhananya seperti yang diungkap oleh para ulama adalah kerinduan nabi Musa akan kampung halaman juga rindu dengan ibunya yang juga tidak diketahui apakah ibunya masih hidup atau sudah meninggal dunia.
Di malam hari, malam jumat, musim dingin, bersama istrinya yang baru melahirkan, mereka tersesat jalan, ditengah kegelapan yang dingin itu, Musa melihat cahaya api dari kejauhan, Musa meminta istrinya untuk menetap sebentar, agar Musa bisa memastikan api yang beliua lihat, mudah-mudahan dari sana api bisa dibawa untuk memanaskan badan dan menerangi perjalanan.
Ternyata api tersebut berasal dari sebuah pohon, Musa kaget dan ta’jub melihat keindahan cahaya api yang berada dipohon tersebut, beliau mendekat, lalu tiba-tiba beliau mendengar suara:
إِنِّي أَنَا رَبُّكَ فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى
“Sesungguhnya aku Inilah Tuhanmu, Maka tanggalkanlah kedua terompahmu; Sesungguhnya kamu berada dilembah yang Suci” (QS. Al-Qasash: 2)
Lalu kemudian dilanjutkan dengan dipilihnya Musa sebagai nabi dan rasul Allah swt:
وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَى إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي
“Dan aku telah memilih kamu, Maka dengarkanlah apa yang akan diwahyukan (kepadamu). Sesungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan (yang hak) selain Aku, Maka sembahlah aku dan dirikanlah shalat untuk mengingat aku”(QS. Al-Qasash: 13-14)
Terkait dengan perintah melepas sandal/alas kaki bagi nabi Musa pada waktu itu, setidaknya ada lima pendapat, menurut Imam Al-Qurthubi:[4]
- Pada waktu nabi Musa diangkat menjadi rasul, beliau memakai pakaian; tutup kepala, baju (jubah), dan celana yang terbuat dari bulu domba, namun sandalnya terbuat dari kulit bangaki keledai, sehingga sandal itu dinilai najis, karena terbuat dari kulit hewan yang tidak disembelih, demikian pendapat Ka’ab, Ikrimah dan Qatadah.
- Ali bin Abi Thalib, juga Hasan dan Ibnu Juraij berependapat bahwa perintah itu dimaksudkan agar nabi Musa mendapat berkah dari tanah suci ditempat itu, sehingga kakinya langsung menempel dengan tanah tersebut.
- Ada juga yang berpendapat bahwa perintah itu dimaksudkan agar Musa lebih khsuyuk dan tawadu’ saat bermunajat kepada Allah swt, yang demikian juga sama halnya degan perilku generasi salaf (terdahulu) mereka juga melepas alas kaki saat melakukan tawaf di ka’bah.
- Pendapat lainnya menyebutkan bahwa melepas alas kaki itu dengan maksud sebagai penghormatan. Konon, Imam Malik, tidak menaikai kendaraan (onta) saat berada di Madinah sebagai perhormatan beliau terhadap tanah Madinah yang didalamnya banyak terdapat mayat orang-orang yang mulia. Inilah makna yang diperoleh dari perkataan Rasulullah saw kepada Basyir bin Khasashiyah ketika beliau berjalan diseputaran kuburan memakai sandal:
إِذَا كُنْتَ فِي مِثْلِ هَذَا الْمَكَانِ فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ
“Jika kamu, wahai Basyir, berada pada tempat semisal ini, maka lepaslah alas kakimu”
- Pendapat kelima ada yang mengungkap bahwa maksud melepas alas kaki itu sebagai isyarat agar nabi Musa bisa fokus menerima perintah Allah swt, dan semenara waktu “lupakan” sebentar istri dan anak ditinggal tadi.
[Ketiga]
Dalam banyak refresensi fiqih kita akan menemukan bahwa ayat diatas (QS. Thaha: 14) pernah dibaca oleh nabi Muhammad saw dihadapan para sahabat dalam kaitannya dengan perhatian terhadap perkara shalat fardhu.
Lebih jelas, Imam Tirmidzi[5] dan Nasai[6] meriwayatkan sebuah cerita kepada kita semua, cerita Rasulullah saw “tertinggal” shalat pada waktunya, bukan karena males, bukan juga karena lesu, tapi karena kondisi peperangan yang sangat menyibukkan mereka dari menghadapi musuh-musuh Allah, yang pada waktu itu terjadi para perang khondaq. Bahkan tidak tanggung-tangung, hingga empat waktu shalat terlewatkan.
Dari Nafi’ dari Abi Ubaidah bin Abdillah, dari Abdullah bin Masud, telah berkata Abdullah:
إِنَّ المُشْرِكِينَ شَغَلُوا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَرْبَعِ صَلَوَاتٍ يَوْمَ الخَنْدَقِ، حَتَّى ذَهَبَ مِنَ اللَّيْلِ مَا شَاءَ اللَّهُ
”Sesungguhnya orang-orang musyrik telah menyibukkan Rasulullah saw sehingga tidak bisa mengerjakan empat shalat ketika perang Khandaq hingga malam hari telah sangat gelap.
فَأَمَرَ بِلَالًا فَأَذَّنَ، ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الظُّهْرَ، ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى العَصْرَ، ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى المَغْرِبَ، ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى العِشَاءَ
Kemudian Rasulullah saw memerintahkan Bilal untuk mengumandangkan adzan diteruskan iqamah, lalu Rasulullah saw mengerjakan shalat dzuhur, kemudian iqamah lagi dan beliau mengerjakan shalat ashar, kemudian iqamah lagi dan beliau mengerjakan shalat maghrib, dan kemudian iqamah lagi dan beliau mengerjakan shalat Isya.”
__________
Dan dalam kejadian yang lainnya, tepatnya pada perang Khaibar, Imam Muslim meriwayatkan bahwa Rasulullah saw dan para sahabat kesiangan, karena beratnya peperangan, sehingga mereka semua terlelap tidur dan sengatan matahari pada akhirnya yang membangunkan mereka.
Ssetelah berwudhu tentunya, Rasulullah saw memerintahkan Bilal untuk iqamah, lalu beliau bersama-sama melaksanakan shalat subuh berjamaah walaupun waktu shalat subuh sudah habis.
Akhir dari segala itu, akhirnya Rasulullah saw mengingatkan kita semua, seperti yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari:[7]
مَنْ نَسِيَ صَلاَةً فَلْيُصَلِّ إِذَا ذَكَرَهَا، لاَ كَفَّارَةَ لَهَا إِلَّا ذَلِكَ {وَأَقِمِ الصَّلاَةَ لِذِكْرِي}
“Siapa saja diantara lupa melaksanakan shalat, maka hendaklah ia mengerjakan shalat tersebut ketika ia ingat, tidak ada tebusan selain dengan melaksanakan shalat tersebut”, kemudian Rasulullah saw membacakan potongan ayat Al-Quran yang berbunyi:
«وَأَقِمِ الصَّلاَةَ لذِّكْري»
“dirikanlah shalat untuk mengingatku” (QS. Thaha: 14)
Dalam riwayat lainnya, Imam Muslim meriwayatkan:[8]
إذا رقد أحدكم عن الصلاة، أو غفل عنها، فليصلها إذا ذكرها
“Jika diantara kalain ada yang tertidur dari melaksanakan shalat, atau lalai (lupa) darinya, maka hendaklah dia mengerjakan shalatnya ketika dia ingat”
Dalam khazah fiqih Islam kita mengenal bab meng-qadha/mengganti shalat yang tertinggal. Shalat jika dikerakan pada waktunya dia disebut dengan ada-an, jika dikerjakan bukan pada waktunya di dikenal dengan ist ilah qadha-an, jika shalat diulang dan dikerjakan pada waktunya maka dia disebut i'adatan.
Para ulama sepakat bahwa jika seseorang meninggalkan shalat karena udzur syar’i; tertidur atau lupa, maka dia wajib meng-qodho/mengganti shalatnya ketika dia sudah bangun dari tidur, atau ketika dia sudah ingat kembali dari lupanya, berapun jumlah shalatnya.
Untuk kasus dimana seseorang “sengaja” meninggalkan shalat, bahkan bertahun-tahun, sehingga ribuan kali shalat dia tinggalkan, disini para ulama juga sepakat bahwa dia berdosa sejumlah shalat yang dia tinggalkan, namun perkara apakah dia “wajib” menggantinya atau tidak, maka disinilah letak perbedaan diatara para ulama.
Kalau mau jujur apa adanya dengan apa yang sudah dibahas oleh para ulama, maka mayoritas ulama menilai bahwa kewajiban mengganti shalat itu berlaku untuk siapa saja dan untuk alasan apapun, baik alasannya lupa/tertidur, atau karena alasan sengaja meninggalkannya. Baik jumlah yang ditnggalkan sedikit maupun banyak.
Ibnu Najim (w. 970 H) salah satu ulama mazhab Hanafi menuliskan dalam kitabnya Al-Bahru Ar-Raiq Syarah Kanzu Ad-Daqaiq sebagai berikut:
أن كل صلاة فاتت عن الوقت بعد ثبوت وجوبها فيه فإنه يلزم قضاؤها سواء تركها عمدا أو سهوا أو بسبب نوم وسواء كانت الفوائت كثيرة أو قليلة
Bahwa tiap shalat yang terlewat dari waktunya setelah pasti kewajibannya, maka wajib untuk diqadha', baik meninggalkannya dengan sengaja, terlupa atau tertidur. Baik jumlah shalat yang ditinggalkan itu banyak atau sedikit.[9]
Ibnu Abdil Barr (w. 463 H) salah satu diantara ulama mazhab Maliki menuliskan di dalam kitabnya, Al-Kafi fi Fiqhi Ahlil Madinah sebagai berikut :
ومن نسي صلاة مكتوبة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها فذلك وقتها
Orang yang lupa mengerjakan shalat wajib atau tertidur, maka wajib atasnya untuk mengerjakan shalat begitu dia ingat, dan itulah waktunya bagi dia.[10]
Asy-Syairazi (w. 476 H) salah satu ulama rujukan dalam mazhab Asy-Syafi'i menuliskan di dalam kitabnya Al-Muhadzdzab sebagai berikut :
ومن وجبت عليه الصلاة فلم يصل حتى فات الوقت لزمه قضاؤها
Orang yang wajib mengerjakan shalat namun belum mengerjakannya hingga terlewat waktunya, maka wajiblah atasnya untuk mengqadhanya.[11]
Ibnu Qudamah (w. 620 H) salah satu ulama rujukan di dalam mazhab Hanbali menuliskan di dalam kitabnya Al-Mughni sebagai berikut :
إذا كثرت الفوائت عليه يتشاغل بالقضاء ما لم يلحقه مشقة في بدنه أو ماله
Bila shalat yang ditinggalkan terlalu banyak maka wajib menyibukkan diri untuk menqadha'nya, selama tidak menjadi masyaqqah pada tubuh atau hartanya.[12]
Memang ada semisal Imam Ibnu Hazm dari madzhab Zhahiri, juga Syaikh Al-Islam Ibnu Taimiyah yang berpendapat bahwa bagi mereka yang “sengaja” meniggalkan shalat tidak wajb menggantinya, namun baginya cukup bertaubat dengan sebenar-benar taubat.[13]
Namun jika ingin lebih aman, tentunya kedua pendapat ini kita ambil dan kita amalkan:
Mula-mula mari bertaubat kepada Allah saw atas dosa besar meninggalkan shalat dengan sengaja yang mungkin selama ini kita lakukan, banyak beristighfar, menyesal dan berusaha untuk tidak meninggalkan shalat lagi apapun kondisinya, lalu kemudian kita cicil dengan cara perlahan sejumlah shalat yang kita tinggalkan, berapapun jumlahnya, semampunya, hingga kita merasa yakin bahwa semua sudah terbayarkan, jikapun maut datang sebelum semunya lunas, setidaknya kita sudah
Berat memang, tapi begitulah kehidupan didunia; penuh dengan beban. Hanya di surga tempat dimana kita bersenang-senang tanpa ada beban dan tanggung jawab lagi.
Wallahu A'lam Bisshawab
---------------------------------------
Referansi:
[1] Ibnu Katsir, Qashash al-Anbiya, hal. 241
[2] Masih menurut Ibnu Katsir, memang terjadi perbedaan pendapat perihal siapa ayah dari kedua perempuan yang ada pada ayat diatas, akan tetapi pendapat terbanyak dan termasyhur menyebutkan bahwa dia adalah nabi Syuaib as, demikian pendapat Al-Hasan Al-Bashri dan Malik bin Anas. (Lihat Ibnu Katsir, Qashash al-Anbiya, hal. 242.
[3] Ibnu Katsir, Qashash al-Anbiya, hal. 243
[4] Al-Qurthubi, Tafsir al-Qurthubi, jilid 11, hal. 172-
[5] At-Tirmidzi, Sunan at-Tirmidzi, jilid 1, hal. 337
[6] An-Nasai, as-Sunan as-Sughra Li an-Nasai, jilid 2, hal. 17
[7] Imam Al-Bukhari, Shahih Al-Bukhari, jilid 1, hal. 122
[8] Imam Muslim, Shahih Muslim, jilid 1, hal. 477
[9] Ibnu Najim, Al-Bahru Ar-Raiq Syarah Kanzu Ad-Daqaiq, jilid 2, hal. 86
[10] Ibnu Abdil Bar, Al-Kafi fi Fiqhi Ahlil Madinah, jilid 1, hal. 223
[11] As-Syairazi, Al-Muhadzdzab, hal. 106
[12] Ibnu Qudamah, Al-Mughni, jilid 1, hal. 439
[13] Lihat: Ibnu Hazm, Al-Muhalla, jilid 2, hal. 10, Ibnu Taimiyah, al-Ikhtiyarat al-Fiqhiyyah, jilid 1, hal. 404