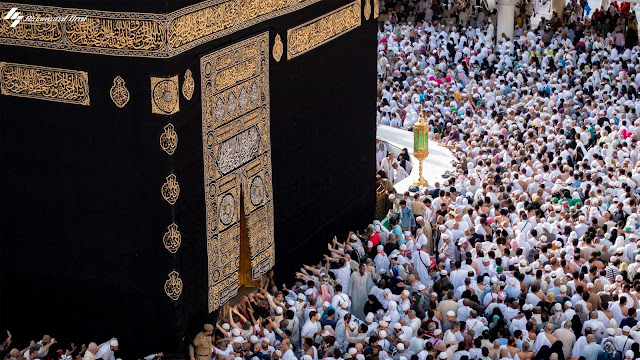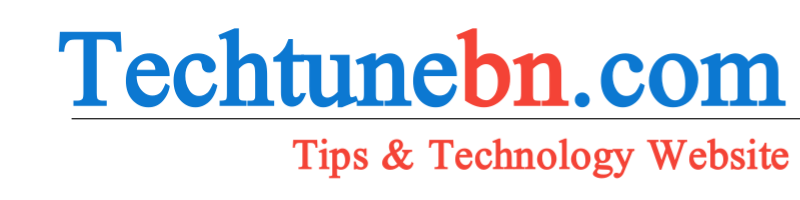Khitan bagi anak perempuan tidak semasyhur khitan yang dilakukan pada anak laki-laki. Jika khitan pada anak laki-laki adalah menyunnat kulup dari batang dzakar (penis), maka tindakan khitan pada anak perempuan adalah menyunnat bagian 'clitoral hood'.
Menurut Wikipedia: "Clitoral Hood atau disebut juga preputium clitoridis and clitoral prepuce adalah lipatan kulit yang mengelilingi dan melindungi clitoral glans [batang klitoris]. Berkembang sebagai bagian dari labia [bibir]minora dan merupakan homolog dari kulup penis [biasa disebut preputium] pada kelamin laki-laki".
Dalil yang menjadi dasar pensyariatan khitan adalah sebagai berikut:
- Kemudian kami wahyukan kepadamu untuk mengikuti millah Ibrahim yang lurus (QS. An-Nahl: 23).
- Dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah SAW, "Khitan itu sunnah buat laki-laki dan memuliakan buat wanita." (HR. Ahmad dan Baihaqi)
- Dari Abi Hurairah ra. Berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda : “Nabi Ibrahim as. Berkhitan saat berusia 80 tahun dengan qadur / kapak. (HR Bukhari dan muslim)
- Dari Aisyah ra, Rasulullah bersabda : “Potonglah rambut kufur darimu dan berkhitanlah” (HR. Muslim)
Dari dalil-dalil diatas, khitan bagi anak perempuan jelas disyariatkan. Namun jika ditinjau dari hukumnya, para ulama fiqih berbeda pendapat. Ada yang mengatakan wajib, tidak wajib, dan ada juga yang memandang itu pemuliaan atas perempuan.
1. Mazhab Al-Hanafiyah
Madzhab ini sepakat bahwa berkhitan tidak diwajibkan bagi perempuan, mayoritas ulama dari madzhab ini tidak memandangnya dari kacamata hukum taklifi, namun sebagai kemuliaan bagi perempuan.
Ibnul Humam (w. 681 H) salah satu ulama mazhab Al-Hanafiyah dalam kitab Fathul Qadir menuliskan sebagai berikut :
الختانان موضع القطع من الذّكر والفرج وهو سنّةٌ للرّجل مكرمةٌ لها
Khitan itu memotong sebagian dari zakar (kemaluan laki-laki) dan farji (kemaluan perempuan). Hukumnya Sunnah bagi laki-laki, dan bagi perempuan merupakan sebuah kemuliaan.
Az-Zaila’i (w. 743 H) salah satu ulama mazhab Al-Hanafiyah dalam kitab Tabyin Al-Haqaiq Syarh Kanzu Ad-Daqaiq menuliskan sebagai berikut :
وختان المرأة ليس بسنة، وإنما هو مكرمة للرجال لأنه ألذ في الجماع
Tidaklah sunnah bagi perempuan berkhitan, tetapi sebuah kemuliaan bagi laki-laki, karena dapat menambah keintiman dalam berhubungan suami istri.[1]
2. Mazhab Al-Malikiyah
Al-Qarafi (684 H), salah satu ulama di kalangan mazhab Al-Malikiyah menuliskan dalam kitabnya Adz-Dzakhirah sebagai berikut :
كرهه مالك يوم الولادة ويوم السابع لأنه من فعل اليهود قال وحد الختان الأمر بالصلاة من سبع سنين إلى عشر قال ابن حبيب الختان سنة للرجال مكرمة للنساء
Makruh bagi imam Malik mengkhitan anak pada hari kelahiran ataupun hari ke tujuh, Karena itu perbuatannya orang-orang Yahudi. Dan membatasi usia khitan ketika anak berumur 7 tahun, sebagaimana diperintah untuk mereka shalat dari umur tujuh tahun hingga sepuluh tahun. Ibnu Hubaib mengatakan, berkhitan bagi laki-laki sunnah, sedangkan bagi perempuan merupakan kemuliaan.[2]
Al-Hathab Ar-Ru'aini (954 H), salah satu ulama di kalangan mazhab Al-Malikiyah menuliskan dalam kitabnya Mawahibul Jalil fi Syarhi Mukhtashar Khalil sebagai berikut :
وأما الخفاض فقال ابن عرفة والخفاض في النساء الرسالة مكرمة وروى
Adapun khitan bagi perempuan, Ibnu ‘Arafah mengatakan bahwa itu adalah syari’at yang mulia.[3]
3. Mazhab Asy-Syafi’i
Madzhab ini memandang bahwa berkhitan bagi laki-laki dan perempuan itu hukumnya wajib. Sebagaimana penuturan di bawah ini:
An-Nawawi (w. 676 H) salah satu ulama dalam mazhab Asy-Syafi'iyah di dalam kitabnya Minhaj At-Thalibin wa Umdatu Al-Muftiin fi Al-Fiqh menuliskan sebagai berikut :
ويجب ختان المرأة بجزء من اللحمة بأعلى الفرج والرجل بقطع ما يغطي حشفته بعد البلوغ ويندب تعجيله في سابعة
Wajib bagi perempuan berkhitan, dengan memotong sebagian daging kecil yang berada di bagian atas kemaluan, dan bagi laki-laki dengan menghilangkan sebagian kulit penutup bagian depan dari kemaluan, dan disunnahkan bagi laki-laki untuk menyegerakan khitan di umur tujuh tahun.[4]
Zakaria Al-Anshari (w. 926 H) yang juga ulama mazhab Asy-syafi'iyah di dalam kitabnya Asnal Mathalib Syarah Raudhu Ath-Thalib menuliskan sebagai berikut.
(و) من (قطع شيءٍ من بظر المرأة) (الخفاض) أي اللّحمة الّتي في أعلى الفرج فوق مخرج البول تشبه عرف الدّيك، وتقليله أفضل
Dengan memotong sebagian daging kecil -yang berada di bagian atas farji, letaknya diatas tempat keluarnya urin, dan bentuknya menyerupai jengger ayam-, itu hukumnya afdhal (utama).[5]
Ibnu Hajar Al-Haitami (w. 974 H) salah satu ulama mazhab Asy-Syafi'iyah di dalam kitab Tuhafatu Al-Muhtaj menuliskan sebagai berikut :
ويجب أيضًا (ختان) المرأة والرّجل
Diwajibkan juga berkhitan bagi perempuan dan laki-laki .[6]
Al-Khatib Asy-Syirbini (w. 977 H) salah satu ulama mazhab Asy-Syafi'iyah di dalam kitab Mughni Al-Muhtaj menuliskan sebagai berikut :
(ويجب ختان المرأة بجزءٍ) أي قطعه
Diwajibkan berkhitan bagi perempuan, dengan menghilangkan sebagian daging kecil di atas kemaluannya.[7]
4. Mazhab Al-Hanabilah
Adapun madzhab Al-Hanabilah, hukum berkhitan dibedakan antara laki-laki dan perempuan. Wajib bagi laki-laki, dan tidak wajib bagi perempuan.
Ibnu Qudamah (w. 620 H) ulama dari kalangan mazhab Al-Hanabilah di dalam kitabnya Al-Mughni menuliskan sebagai berikut :
فأمّا الختان فواجبٌ على الرّجال، ومكرمةٌ في حقّ النّساء، وليس بواجبٍ عليهنّ
Diwajibkan bagi laki-laki berkhitan, sedangkan bagi perempuan tidaklah diwajibkan, melainkan hanya sebuah kemuliaan bagi yang mengerjakannya.[8]
Kesimpulan
Demikian pemaparan para ulama dari empat madzhab. Madzhab Syafi’i mengatakan bahwa hukum khitan itu wajib atas laki-laki maupun perempuan. Sedangkan madzhab Hanafi, Maliki dan Hambali tidak memandang khitan atas perempuan dari sisi hukum taklifi, melainkan dari sisi afdhaliyyah (keutamaan). Ketiga madzhab tersebut mengatakan bahwa khitan yang dilakukan pada anak perempuan merupakan tindakan pemuliaan Islam atas perempuan.
Wallahu a’lam bishshawab
[1] Az-Zaila'i, Tabyin Al-Haqaiq Syarh Kanzu Ad-Daqaiq, jilid 1, hal 227
[2] Al-Qarafi, Adz-Dzakhirah, jilid 4, hal 167
[3] Al-Hathab Ar-Ru'aini, Mawahibul Jalil fi Syarhi Mukhtashar Khalil, jilid 3, hal 258
[4] An-Nawawi, Minhajut Thalibin Wa Umdatul Muftiin, jilid 1, hal 306
[5] Zakaria Al-Anshari, Asnal Mathalib Syarah Raudhu Ath-Thalib, jilid 4, hal 164
[6] Al-Haitami, Tuhfatul Muhtaj bi Syarhi Al-Minhaj, jilid 9, hal 198
[7] Al-Khatib Asy-Syirbini, Mughni Al-Muhtaj , jilid 5, hal 539
[8] Ibnu Qudamah, Al-Mughni, jilid 1, hal 64